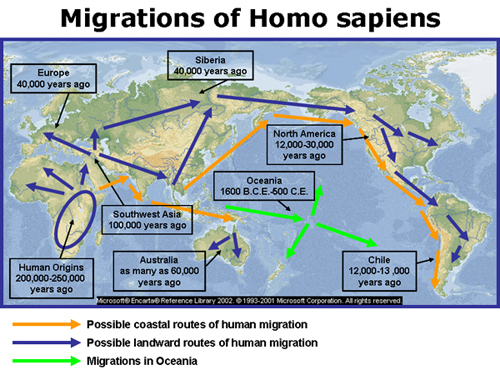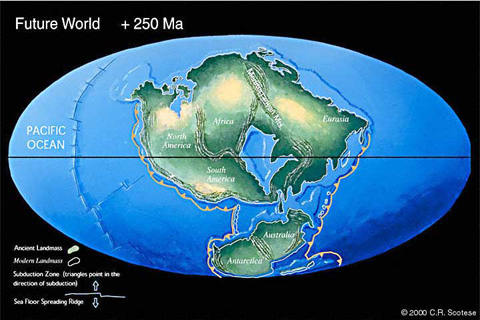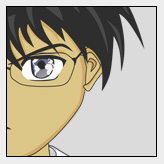Update Juni 2014: Sebagian posting telah diset privat.
Saya pertama kali menulis blog sekitar bulan Mei 2006, pertama-tama di livejournal, kemudian pindah ke blog WordPress yang sekarang. Waktu itu saya masih kuliah tingkat dua, dan kalau boleh dibilang, menulisnya benar-benar santai: pakai kata ganti gw-lo, banyak membahas keseharian, dan isinya cenderung personal. Hampir tidak ada tulisan panjang-lebar yang serius. Bolehlah dianggap bahwa itu masa-masanya saya masih kroco di dunia blog. Tapi soal itu sebaiknya tak dibahas di sini.
Nah, yang hendak dibicarakan di sini terkait dengan masa-masa awal ketika baru pindah ke WordPress. Saya mulai menulis di sini sekitar bulan Desember, jadi, kurang lebih sekitar 6 bulan sejak awal ngeblog. Kalau dihitung-hitung: persis sudah empat tahun saya menulis di alamat ini.
Dulu di tahun 2006-07, banyak blogger hebat yang menulis di WordPress, di antaranya Bang Aip, Mas Fertob, Mas Joe, dan Kang Tajib. Sekarang hampir semua punya hosting pribadi. Lalu ada blog Wadehel yang — waktu pertama kali baca — sempat bikin kaget dan rada trauma. Walaupun begitu belakangan saya mulai bisa memahami maksud di balik tulisannya, so that’s fine. 😛
Lalu saya juga ketemu banyak teman yang luar biasa. Dari yang (waktu itu) masih SMA sampai yang sudah bapak/ibu dan berkeluarga, semuanya menarik dan enak diajak ngobrol. Ada begitu banyak nama sampai-sampai tak bisa disebut satu-persatu. Mulai dari generasinya kgeddoe dan mas Gun; generasi saya sebangsa mbak Hiruta dan Chika; lalu yang lebih muda generasinya xaliber; generasinya mas Amed–Farid–Mansup… sampai yang sudah paruh baya seperti bu Evy dan Kang Tajib di atas. Banyak di antaranya yang sudah berhenti ngeblog atau pindah website. Bagaimanapun itu hal yang wajar. Empat tahun itu waktu yang lama.
Menariknya adalah, selama empat tahun itu, saya bisa dibilang tak pernah ganti-ganti identitas. Sejak dulu ya, kalau orang melihat saya di blogosphere, pasti namanya sora9n. Sejak dulu mayoritas isi blog saya bertema J-stuffs, opini serius, atau ngobrol tentang sains. Dan sejauh saya ingat, blog ini hampir tak pernah ganti tampilan — ganti theme cuma sekali; ganti header dan tampilan sidebar pun demikian. Ibaratnya: kalau Anda pernah berkunjung ke sini dua tahun lalu, lalu baru main ke sini lagi, dijamin panglingnya cuma sedikit.
Akan tetapi sebagaimana halnya benda di dunia ini, tidak ada yang abadi. Hal-hal di sekitar saya berubah; garis besar pemikiran saya juga berubah. Sementara apa yang ada di blog ini sudah mengkristal pencitraannya: bahwa saya begini-dan-begitu, bahwa blog ini *diasumsikan* isinya begini-dan begitu. Jadi saya berpikir begini. Barangkali sudah waktunya saya mencoba mengakomodasi perubahan itu.
Saya, misalnya, semenjak tahun 2009 sudah tak rajin mengikuti barang-barang Jepang. Saya tidak tahu anime atau dorama terbaru, juga tidak tahu kabar J-music terbaru (walaupun saya masih menulis seri nihongo di blog ini; tapi itu sekadar melanjutkan yang sudah ada saja). Haluan filosofis saya juga berubah: dari yang tadinya religius-liberal (c. 2006) menjadi teis agnostik (c. 2007) hingga sekarang agnostik tanpa embel-embel (sekitar akhir 2007? lupa 😛 ). Semua perubahan itu tercermin di berbagai rangkaian posting di blog ini. Dari masa ke masa garis besar haluan ngeblog saya terus berubah dan, di saat ini, saya telah berjalan begitu jauh — sedemikian hingga ada perbedaan yang visible antara diri saya dulu dan sekarang.
Masalahnya adalah bahwa blog ini menimbulkan ekspektasi pada pembacanya. Kalau orang dengar istilah “blog sora-kun” barangkali yang terlintas adalah: “blog yang suka ngomong jejepangan, teori evolusi, atau coretan keseharian“. Sementara ada banyak hal yang ingin saya eksplorasi di luar itu yang belum tentu cocok dengan audiens.
Jadi saya menetapkan bahwa Garis Besar Haluan Ngeblog (GBHN) saya telah berubah. Saya ingin membicarakan hal lain; saya ingin mengomunikasikan hal-hal berbeda dengan segmen pembaca yang (boleh jadi) juga berbeda. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti ngeblog di sini dan melanjutkan di blog yang baru.
Link dan banner dari blog tersebut
Yup, that’s about it. Jadi, setelah empat tahun ngeblog di alamat ini, saya akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Masih di bawah pengawasan bapak kos Oom Matt di WordPress, cuma beda nomor kamarnya sahaja. Silahken dikunjungi atau di-subscribe kalau berkenan. 😛 biarpun isinya sejauh ini baru dua posting
Jadi, ada apa di blog baru ini?
Rencananya di blog tersebut saya akan lebih banyak merilis tulisan bertema serius; kira-kira seperti terkandung di kategori deeper thoughts. Berhubung pendidikan saya teknik maka temanya akan berkisar antara sains dan engineering — walaupun bukan tak mungkin bakal ada tulisan nyerempet ilmu sosial. Bagaimanapun memang dua bidang itu sering bertabrakan. 😛 (see also: teori evolusi, antropologi)
Rencananya saya juga ingin mencoba gaya menulis baru di sana. Alih-alih membuat tulisan panjang-lebar tapi jarang update seperti di blog ini, saya akan lebih fokus pada posting pendek-tapi-rutin. Sebisa mungkin tidak lebih dari 1000 kata; jikapun lebih, sungguh mati tiada maksud. Mudah-mudahan masih bisa ditoleransi kalau kepanjangan. 😛 Harapannya sih bisa rajin update sambil tetap menjaga mutu.
Wrapping it up…
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada pembaca yang sudah menyambangi blog ini selama empat tahun terakhir. Mulai dari yang rajin berkunjung dan berkomentar; yang sekadar membaca tanpa komentar; yang sampai ke blog ini lewat link; sampai yang tersasar ke sini gara-gara google. Semua hits itu telah membantu menyemangati saya selama mengisi tulisan di blog ini.
Sebagai informasi, rata-rata harian kunjungan blog ini sejak tahun 2007 adalah 183, 328, 412, dan 335. Semuanya disumbang oleh kehadiran, diskusi, dan link balik para pembaca.
Oleh karena itu, menutup perjalanan panjang di blog ini: terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Terima kasih banyak, sebanyak kunjungan Anda semua ke blog ini. m_(u_u)_m *plak*
Komentar akan tetap dibuka sampai Tahun Baru 2011, setelah itu akan ditutup untuk seterusnya. Silakan meninggalkan pendapat, kesan-pesan, atau sebagainya — sejauh tidak melanggar rambu-rambu berkomentar, respon anda akan diterima dengan baik.
Akhir kata, terima kasih banyak, dan sampai jumpa. Adios!
— SHQM
Addendum:
Saya merasa agak terbebani karena — sejauh saya ingat — ada tulisan yang bersifat hutang dan tak pernah dilunasi sampai blog ini tutup. Yang pertama kelanjutan seri nihongo; ada banyak sekali materi yang tak sempat saya tulis. Yang kedua bagian penutup seri mekanika kuantum: semestinya sudah ditamatkan pada awal tahun 2009, akan tetapi sampai sekarang ternyata terbengkalai. Untuk ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. ^:)^
Saya menulis dua bidang tersebut semata dengan semangat Free Culture — saya percaya bahwa ilmu pengetahuan selayaknya disebarkan seluas mungkin tanpa diambil untung. Akan tetapi untuk menulisnya butuh waktu dan energi yang lumayan, dan itu adalah hal yang jarang saya miliki dalam dua tahun terakhir.