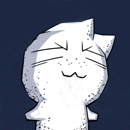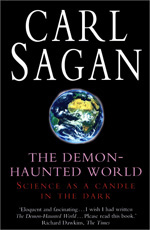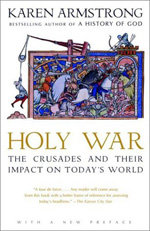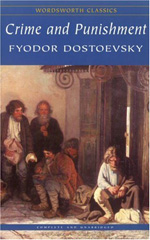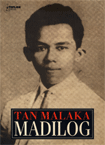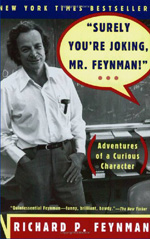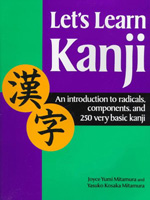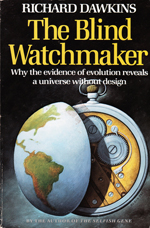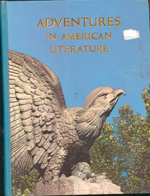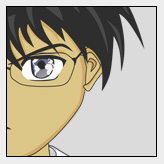Sedang jalan-jalan di Facebook kemarin siang, saya menemukan sebuah page yang menarik. Isinya sendiri bisa dibilang jejaring sosial banget — tidak jauh beda dengan urusan tag-mengetag pada umumnya. 😛
Take no more than 15 minutes, and make a list of the 15 books that stick with you, for whatever reason. Then spread the list:
— Post your list here
— Post it on your profile for your friends to see
— Become a fan of this page
— Include a link to http://www.facebook.com/15books in your profile post
Saya pikir, kalau ditulis sebagai notes, tidak semua orang bisa baca — harus daftar FB, add friend, dan seterusnya — sementara saya orangnya tidak mau approve sembarangan. Walhasil, saya pun memutuskan untuk menulisnya di blog saja. 
Seperti apa daftarnya, here goes…
(CATATAN: hampir semua dari buku di bawah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, meskipun demikian saya merujuk pada versi dalam bahasa aslinya)
1. “Demon-Haunted World: Science as A Candle in The Dark”
— Carl Sagan (1995)
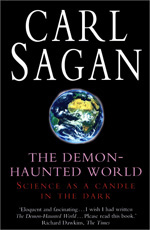
Buku yang berisi kumpulan esai oleh almarhum Carl Sagan. Kalau boleh jujur, Pak Sagan adalah salah satu ilmuwan yang paling saya kagumi: berpengetahuan luas, punya kesadaran sosial, juga piawai mempopulerkan sains di masyarakat umum. Buku ini merangkum berbagai sudut pandang beliau semasa hidupnya (1932-1996).
Personal Rating:





2. “A History of God”
— Karen Armstrong (1993)

Pertama kali baca buku ini waktu kelas 2 SMA. Pertama-tama kebingungan — meskipun begitu, setelah beberapa waktu, mulai bisa memahami alurnya. 😛 Berkisah tentang evolusi keyakinan manusia sejak zaman pagan hingga era modern. Ini buku yang memperkenalkan saya pada gagasan ber-Tuhan yang esoterik; juga membuka mata bahwa “iman” itu banyak ragamnya.
Personal Rating:





3. “Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World”
— Karen Armstrong (1988)
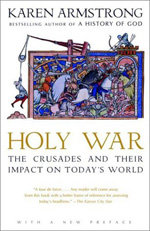
Buku kedua dari Karen Armstrong di daftar ini, sekaligus juga yang terakhir. Dalam buku ini Bu Armstrong berkisah tentang kronologi Perang Salib dan dampaknya di era modern. Buku ini sempat membuat saya kecewa berat — bukan karena isinya jelek, melainkan karena sukses membuat depresi. Pengantar saya sebelum membaca literatur Perang Salib yang lebih serius (Runciman, Hillenbrand — tidak dibahas di daftar ini).
Personal Rating:





4. “Manusia Multidimensional: Sebuah Renungan Filsafat”
— M. Sastrapratedja (ed.) (1982)

Buku jadul lungsuran ibu saya, meskipun begitu sepertinya beliau tidak pernah baca. ^^;; Berbentuk kumpulan esai, buku ini mengantar saya pada ide-ide dasar filsafat barat. Pertama kali “mengenal” Nietzsche, Jaspers, dan Camus dari buku ini — walaupun begitu, pembahasannya tentang Popper paling mengena di hati saya. Dus, membuka jalan saya untuk belajar filsafat lebih jauh. I’m eternally grateful to the authors of this book.
Personal Rating:





5. “Crime and Punishment”
— Fyodor Dostoyevski (1866)
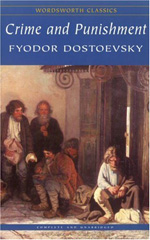
Novel penulis Rusia pertama yang saya baca; waktu itu saya hampir lulus SMA. Banyak pesan moral yang saya dapat dari buku ini. Meskipun begitu ada satu poin yang paling berkesan: orang tidak bisa bahagia jika hanya bermodal rasionalitas (Raskolnikov) atau kehangatan hati semata (Sonia). Agar orang bisa bahagia, harus ada keseimbangan di antaranya, dan itu dicontohkan secara apik lewat “jalan” Razumihin dan Dounia.
Personal Rating:





6. “Madilog”
— Tan Malaka (1943)
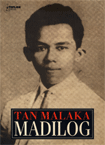
Saya pertama kali tahu Tan Malaka lewat autobiografi Dari Penjara ke Penjara, jilid II, sekitar tahun 2003-04. Oleh karena itu, saya tahu sedikit tentang Madilog — dan kemudian, ketika ada teman kos yang punya, saya pun meminjam dengan sukses.  Dengan materi ilmu alam, logika, dan filosofi yang dibawanya, buku ini turut membentuk pemikiran saya di awal kuliah. (walaupun efeknya tidak sedahsyat Demon-Haunted World)
Dengan materi ilmu alam, logika, dan filosofi yang dibawanya, buku ini turut membentuk pemikiran saya di awal kuliah. (walaupun efeknya tidak sedahsyat Demon-Haunted World)
Personal Rating:





7. “Anak Semua Bangsa”
— Pramoedya Ananta Toer (1981)

Bagian kedua dari Tetralogi Buru, sekaligus yang paling berkesan secara pribadi. Humanisme lintas batas yang dicerminkan para tokohnya benar-benar strike di hati saya. Mulai dari Jawa (Minke, Nyai), Tionghoa (Khouw Ah Soe), hingga Eropa (Jean Marais dan keluarga Delacroix), semua sepakat bahwa tidak ada manusia yang suka ditindas. Kisah perjuangan bangsa Filipina dan Cina oleh Khouw Ah Soe jadi pelengkap yang manis.
Novel karya mbah Pram ini sukses mengingatkan saya pada nilai yang berharga: Kemanusiaan itu universal, tidak terkotak-kotak oleh suku dan ras. Mengutip H.G. Wells, “Our true nationality is mankind.”
Personal Rating:





8. “Surely You’re Joking, Mr Feynman!”
— Ralph Leighton & Richard Feynman
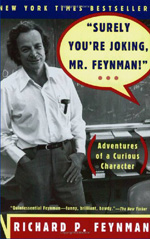
Setelah dari tadi membahas buku serius, maka sekarang waktunya buku yang lebih ceria. 😀
Surely You’re Joking, Mr Feynman! adalah sebuah (semi-) autobiografi karya Nobelis fisika Richard Feynman. Meskipun begitu, alih-alih membahas rumus dan dunia fisika, buku ini memberi gambaran dari sisi lain: bagaimana keseharian Feynman, rasa penasarannya akan segala hal, dan hobinya mengisengi teman sejawat. Sifat Feynman yang cerdas-tapi-playful adalah sumber inspirasi saya. Malah dulu saya bercita-cita mengikuti jejak beliau jadi ilmuwan! 😀
Menurut saya, buku ini seolah mencibir stereotip “orang jenius” yang berlaku di masyarakat dan menguburnya dalam-dalam. Listen now, kids: nobody likes a snobby genius! 
Personal Rating:





9. “Lets Learn Kanji: An Introduction to Radicals, Components and 250 Very Basic Kanji”
— Y.K. Mitamura et. al. (1997)
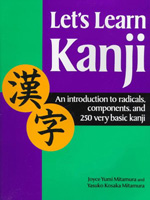
Buku pengantar saya belajar Kanji. Kalau boleh jujur, saya sebenarnya tidak punya patokan khusus belajar Bahasa Jepang — ada banyak buku yang saya baca. Meskipun begitu yang satu ini benar-benar stand out sehingga layak disebut tersendiri. Dengan penjelasan, organisasi, dan trik memorization yang mantap, buku ini layak dimiliki oleh setiap peminat barang-barang Jepang.
Personal Rating:





10. “Concepts of Modern Physics”
— Arthur Beiser (1981)

Pembaca serial mekanika kuantum di blog ini mungkin sudah tahu buku di atas. Buku ini sempat saya cantumkan sebagai salah satu referensi di sana. Ilustratif, mengedepankan konsep, dan (relatif) sedikit bermain rumus, buku ini merupakan pengantar yang bagus menuju dunia fisika modern — di antaranya teori relativitas, mekanika kuantum, dan fisika partikel. Satu-satunya buku kuliah yang suka saya baca jika sedang senggang. 😛
Personal Rating:





11. “The Blind Watchmaker”
— Richard Dawkins (1986)
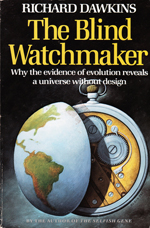
Salah satu pengantar terbaik dalam memahami Teori Evolusi. Dalam buku ini, Dawkins menjelaskan bagaimana keragaman yang kompleks dapat dicapai lewat perubahan yang berkesinambungan (evolusi). Konsep-konsep rumit seperti DNA, mutasi, dan pewarisan dijelaskan lewat analogi yang mudah dicerna. Buku ini adalah salah satu awalan saya dalam mempelajari teori evolusi. (yang satu lagi buku S.J. Gould di nomor 12)
Personal Rating:





12. “Structure of Evolutionary Theory”
— Stephen Jay Gould (2002)

Buku mammoth yang bisa dipakai membunuh cicak kalau dijatuhkan (seriously). Tebalnya 1343 halaman. Meskipun begitu, jika Anda benar-benar tertarik mendalami evolusi, maka buku ini adalah pilihan yang bagus. Sekitar separuhnya — 600-700 halaman — dialokasikan untuk membahas sejarah pemikiran, dan sisanya penjelasan teknis.
Dilengkapi gambar, foto, dan analogi oleh salah satu palaeontolog paling masyhur di dunia. Long story short, buku ini membuat Gould jadi “menara kembar” pemahaman evolusi saya — bersama dengan Richard Dawkins yang disebut sebelumnya. 😛
Personal Rating:





13. “Adventures in American Literature (Classic Edition)”
— James Early et. al. (ed), various American writers
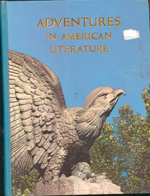
Buku ini merupakan kompilasi cerpen dan puisi karya penulis Amerika dari zaman ke zaman, mulai dari era Wild West hingga awal abad 20. Karya penyair legendaris seperti Edgar Allan Poe, Longfellow, dan Nathaniel Hawthorne bisa dibaca di sini. Terdapat juga sketsa biografis dan analisis komposisi berbagai karya tersebut; tambahan yang menarik untuk orang yang latar belakangnya non-sastra seperti saya.
Personal Rating:





14. “Fantasista”
— Michiteru Kusaba (1999-2006)

Manga pertama di daftar 15 Books ini. Saya bisa dibilang bukan peminat manga hardcore — saya tidak langganan majalah sebangsa ShonenMagz, jarang download, juga jarang beli di kios. Meskipun begitu Fantasista adalah pengecualian. Ilustrasinya bagus, jalan ceritanya menarik, dan teknik bermain bola yang disajikan tergolong realistis. Tidak ada tendangan maut a la Shoot! atau Captain Tsubasa. Pokoknya, sepakbola as we know it! 
Sayangnya serial ini memiliki ending yang buruk. Kesannya kurang dipoles, begitu, sehingga saya tak bisa memberi nilai sempurna. Oh well.
Personal Rating:





15. Q.E.D ~証明終了~
— Motohiro Katou (1997–present)

Yup, you read it right. Another manga in this list. Tak lain dan tak bukan, manga yang tokoh utamanya sosok jenius lulusan MIT. Siapa lagi kalau bukan So Toma? 
Bagi saya, Q.E.D. adalah salah satu komik favorit sepanjang masa. Komik ini berkisah tentang seorang jenius yang sulit dipahami oleh lingkungan sekitarnya, meskipun begitu, belakangan ia mulai bekerja sebagai detektif paruh waktu. Kasus yang ditangani Toma umumnya berhubungan dengan tema ilmiah seperti matematika, seni, dan sejarah — hal yang membuat komik ini jadi menarik. Malah saya tahu hal-hal obscure seperti Jembatan Konigsberg dan legenda Pygmalion dari komik ini! 😀 So that’s saying much. Manga ini masih berjalan sampai sekarang, dan di Indonesia diterbitkan oleh Elex Media Komputindo.
Personal rating:





***
Yah, kurang lebih seperti itu daftarnya. Tiga belas buku serius (baca: isinya sebagian besar tulisan) dan dua buah komik. Sebenarnya bukan tak mungkin ada yang terlewat, tapi, hei, yang disuruh kan cuma yang teringat saja. 😆
BTW, saya tidak mengetag siapapun untuk mengerjakan tugas ini. Silakan kalau ada pembaca yang berminat melaksanakan — tergantung suasana hati sajalah. 😉 Walaupun saya penasaran juga sih daftar bukunya lambrtz, geddoe, dan mas gentole seperti apa…
Read Full Post »
Tapi itu cerita lain untuk saat ini.