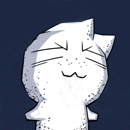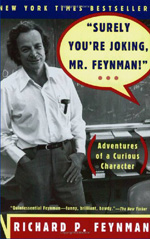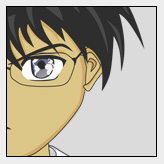Kalau boleh menilai diri sendiri, saya bisa dibilang orang yang berjiwa insinyur (walaupun punya keberatan pada kuliahnya, tapi itu cerita lain). Bagaimanapun ini bukan hal yang aneh. Sebagai orang yang sekian tahun belajar di jurusan teknik, sudah pasti ada pengaruh yang meresap. Ini sifatnya psikologis: orang-orang di sekitar saya berpikir secara engineering, maka saya jadi ikut terbawa. Kurang lebih seperti itu.
Beberapa pembaca mungkin kurang akrab dengan dunia yang disebut, jadi ada baiknya saya cerita sedikit dulu.
Di dunia insinyur, tuntutan utamanya adalah “bagaimana agar hidup manusia jadi lebih mudah.” Misalnya insinyur elektro; mereka berupaya memudahkan hidup orang yang terkait listrik (misal: desain pembangkit listrik, pengkabelan, dsb.) Insinyur sipil berupaya memudahkan hidup orang dengan bangun-membangun, dan seterusnya. Kasar-kasarnya: kalau dokter punya job description menyehatkan orang, maka insinyur punya job description membuat orang jadi nyaman.
Nah, upaya “membuat orang nyaman” di atas adalah hal yang rumit. Namanya insinyur sudah tentu bekerja dengan teknologi. Ada yang lewat teknologi listrik, mesin, atau lain sebagainya. Semuanya bekerja menghasilkan penemuan lewat teori dan perhitungan. Teori dan perhitungan bagi insinyur, ibaratnya batu bata untuk tukang bangun rumah: elemen penting yang dipakai untuk membangun. Kalau ada itu, semua jadi gampang. Nah tapi ada masalah.
Biarpun insinyur punya seperangkat hukum fisika dan matematika yang bisa dipakai, pengerjaannya tidak mudah. Banyak hambatan yang membuat teori kita jadi tidak sesuai, harus diperbaiki sedikit — biarpun dasarnya sudah benar. Misalnya seperti berikut.
Dalam ilmu fisika, terdapat aturan yang disebut Hukum Bernoulli. Ini adalah hukum yang mengatur jalannya aliran fluida.
Seorang insinyur diminta untuk meneliti aliran limbah dalam pipa. Langsung saja dia hitung dengan Hukum Bernoulli. Ternyata hasil perhitungannya salah! Padahal matematikanya sudah benar, tapi kenapa begitu?
Penyebabnya: karena Hukum Bernoulli cuma berlaku untuk fluida ideal, semisal air murni. Sementara limbah umumnya campur-baur antara padatan, air, dan gas — jauh sekali dari ideal. Jadi perhitungannya tidak menghasilkan apa-apa.
Saya dan teman-teman suka berkelakar soal ini, dan bilang: “Tuh lihat, di dunia ini tidak ada yang ideal. Teori sebagus apapun pasti meleset — jadi pelajaran kita itu aslinya gak guna.”
Tentunya yang di atas itu cuma bercanda. But you get the point. 😛
Ini problem yang selalu menghantui para insinyur di bidang manapun. Teori yang sempurna itu tidak ada. Sedikit-banyak pasti ada kompromi. Bisa saja idenya benar, teorinya benar, dan seterusnya — tapi, di dunia nyata, namanya gangguan itu pasti ada. Entah nilainya besar atau kecil. Tidak mungkin ada sistem di lapangan yang 100% sesuai teori. No way!
Ini mirip membandingkan soal fisika yang dikerjakan anak SMA dengan fisika sebetulnya. Di SMA kita disuruh mengerjakan soal, tapi dalam kondisi ideal: tidak ada hambatan udara, tidak ada gesekan, dan sebagainya. Sementara kondisi sebenarnya tidak begitu. Seringnya sih dunia nyata lebih rumit daripada dijelaskan dalam buku.
Teman saya yang anak elektro pernah cerita tentang Arus Eddy yang mengganggu voltmeter. Lain kali, dosen dari jurusan mesin cerita tentang oli: jadi ada oli masuk mesin, mempengaruhi bensin yang aslinya hendak dibakar. Walhasil output energinya berkurang. Hal-hal semacam itulah. Saya sendiri cengar-cengir saja mendengarnya, sebab, di jurusan saya, hal-hal seperti itu juga terjadi.
Ceritanya saya dan beberapa anggota kelompok pernah praktikum dengan pompa. Sesudah mencatat suhu dan tekanan, datanya harus dihitung dan dibandingkan. Tapi kok perbandingannya tidak cocok? Ternyata ada katup yang ngadat, jadi bukaannya tidak sempurna! Akhirnya aliran air yang dihitung jadi meleset. Baru belakangan si asisten bilang ke anak-anak bahwa alatnya rada terganggu. Tapi secara umum tidak apa-apa — jadi angkanya dikompensasi saja dengan kesalahan sekian-sekian.
Praktikannya sendiri cuma bisa angkat bahu. Mau bagaimana lagi? 😆
***
Jadi, lima atau enam tahun belajar di jurusan teknik mengajari saya satu hal: di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali ide-ide. Teori sebagus apapun, sesempurna apapun, kalau sudah masuk dunia nyata, pasti ada kompromi. Tidak mungkin tidak.
Lalu saya berpikir, jangan-jangan itu juga yang terjadi di ilmu sosial. Bertahun-tahun kita punya teori psikologi, sosiologi, dan ilmu politik, tapi kok kita masih belum paham? Jangan-jangan karena ada banyak elemen yang harus dipertimbangkan di dalamnya, tapi justru terabaikan. Sama halnya dengan kasus arus Eddy dan hukum Bernoulli di atas…
…mungkin. Mungkin lho. Saya kan bukan ahli di bidang itu.
Pada akhirnya, saya sendiri jadi rada skeptis dengan yang namanya “kesempurnaan” atau “100% ini-itu”. Sebab ya, di dunia ini tidak ada yang 100%. Budaya Indonesia, misalnya, tidak 100% Indonesia (ada banyak pengaruh luar juga). Negara yang 100% free market atau sosialis juga tidak ada — yang ada cuma mendekati salah satunya. Tegangan listrik diukur dengan voltmeter, sebagian arusnya ada yang masuk ke voltmeter (jadi akurasinya tidak 100%), dan seterusnya.
Jadi saya pikir, ah kacau nih kalau orang berani bilang, “Sistem pemerintahan sempurna. Dijamin 100% sukses!” Biasanya yang bilang begitu golongan sayap kanan, tapi itu sebaiknya tak dibahas di sini…
***
Di sisi lain, ada juga tidak enaknya dari “didikan” bersikap realistis di atas. Gara-gara itu saya jadi tidak sabaran kalau berurusan dengan orang yang idealis tapi tidak mengerti lapangan. Ini sifatnya universal: tak peduli yang dibicarakan itu politik, sosial, atau keseharian, kalau itu terjadi, biasanya saya jadi mangkel. Perasaan ini susah dijelaskan.
Misalnya waktu ada gerakan “tolak bayar pajak” gara-gara Gayus Tambunan. Saya dongkol betulan waktu itu. Seriously, do they even think? Coba, apa jadinya administrasi negara, kepercayaan investor, dan sebagainya kalau itu terjadi. Ini mirip dengan ilustrasi Hukum Bernoulli di atas: dikiranya dia paham semua masalah, lalu menerapkan teori dari situ — padahal kenyataannya tidak sesederhana yang disangka. Ha!
Lain kali, saya berdebat panas dengan seorang troll soal Israel-Palestina (saya tidak memihak siapa-siapa di situ; ceritanya panjang). Dia bilang HAMAS itulah yang benar. Saya tanya, situ mengerti tidak sejarah geopolitik Yerusalem? Masalahnya bukan sejak 1948 atau khilafah, melainkan sampai zaman Romawi. Eh dia marah. Saya sendiri bukannya tak berusaha kalem, tapi tetap saja…
Hal-hal semacam itulah. Susahnya terbiasa berpikir realistis adalah, kita jadi tidak sabar melihat orang yang naif. Kesannya kok hidup di awan. Idealisme itu bagus, tapi mbok ya diimbangi dengan asupan realitas.
Jadi ini semacam PR juga buat saya. Mengendalikan marah itu gampang, tapi mengendalikan jengkel… wah, susah sekali. Sebab itu tatarannya dalam hati (bukan perbuatan). Saya masih harus belajar banyak soal itu.
Meskipun begitu ada juga dampak positifnya. Gara-gara itu, kalau saya memberi saran, jadinya dipandang sebagai “saran yang bermutu”. Pokoknya sebisa mungkin realistis. Ini berlaku terutama kalau sedang mendengarkan orang curhat — saya sih biasa saja, terserah mereka mau terima atau tidak. Sejauh ini sih mereka selalu mau dengar. 😛
Saya sendiri bersyukur mendapat didikan cara berpikir realistis selama di kampus. Paling tidak sekian tahun di sana telah mengajari saya untuk bersikap membumi… hal yang ternyata merembes ke berbagai aspek lain dalam hidup. But hey, that’s what education is supposed to be, right? 😉