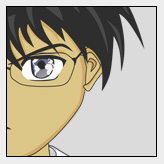Kuba, 1959. Revolusi baru saja meletus, dan Fidel Castro naik tampuk menjadi pimpinan besar di negeri pulau tersebut. Jargon-jargon komunisme bertebaran, dan euforia menguar pasca jatuhnya mantan presiden Batista — ketika, di saat yang sama, kemiskinan dan kerusuhan merajalela. Gelombang eksodus besar-besaran menuju Amerika Serikat menjadi jalan keluar bagi penduduk yang terhimpit, atau bagi mereka yang berseberang jalan politik dengan sang Jendral.
Apa yang terjadi ketika sebuah keluarga Kuba yang biasa, dengan para anggota keluarga yang juga biasa, mulai terkena imbasnya?
Manis, pedih, menusuk, sekaligus mengharukan dalam satu waktu — jika saya disuruh memilih buku terbaik yang saya baca sepanjang liburan ini, maka novel ini adalah kandidat utamanya. 😉

Judul: Broken Paradise – Surga yang HancurPenulis: Cecilia Samartin
Penerbit: OnRead-Books Publisher; cetakan I Maret 2008
Tebal: vi + 360 halaman
The Story
Nora Garcia adalah seorang anak perempuan biasa, dengan keluarga besar yang juga biasa, di salah satu sudut kota Havana. Berangkat ke sekolah Katolik setiap pagi adalah rutinitasnya, dan berlibur ke pantai pasir putih di Varadero adalah selingannya. Ia punya ayah, ibu, paman dan bibi, serta kakek-nenek yang sayang padanya. Di usia sembilan tahun, keluarganya lengkap dan bahagia.
Begitupun, yang paling akrab dengannya adalah saudari sepupunya, Alicia putri Paman Carlos. Gadis yang — di mata Nora — selalu terlihat “cantik, berani, dan pintar”. Sosok yang sama seringnya antara membuat Nora iri ataupun tertawa bahagia… teman yang menemaninya belajar berenang bersama kakek di pantai, hingga debat tak jelas mengenai cinta pertama… atau, lebih tepatnya, segala hal yang umum dimiliki oleh pasangan teman sejak kecil.
Sayangnya kebahagiaan tak berlangsung lama. Di tahun 1959, Fidel Castro menggulingkan Presiden Batista. Revolusi Kuba dimulai. Ikon-ikon gereja diratakan dengan tanah, dan sekolah Katolik ditutup. Kerusuhan dan penahanan oleh pemerintah semakin marak — dan keluarga Nora memutuskan untuk mengajukan visa untuk emigrasi ke Amerika Serikat. Adapun Alicia, bersama dengan Paman Carlos dan istrinya, memutuskan bertahan di tanah air mereka. Bertahan dengan harapan bahwa kekacauan yang diakibatkan Castro hanyalah sementara.
Dan kisah dua keluarga Kuba yang terpisah pun dimulai: yang satu dengan asal-usul yang tercerabut di tanah harapan, dan yang lainnya morat-marit di negeri asal…
***
On My Notes
Sejujurnya, ketika pertama kali membaca novel ini, saya langsung terpikat pada gaya bertuturnya yang sangat filmis. Deskripsi kuat, dengan bumbu kehidupan Kuba pra-revolusi yang terasa asing-tapi-dekat, menjadi nilai plus dari kisah yang satu ini. Mungkin kalau di Indonesia, gaya ini bisa dibandingkan dengan karya Andrea Hirata. Ia menyuguhkan ‘pemandangan’ yang detail ketika, di sisi lain, memberikan insight mendalam tentang keadaan sosial para tokohnya.
Hal yang menjadi kekuatan utama novel ini adalah korespondensi antara Nora dan Alicia yang terjalin selama bertahun-tahun, menjelaskan perbandingan antara kehidupan eksil dengan mereka yang bertahan di bawah rezim Castro. Upaya keluarga Garcia bertahan hidup di California, disertai gegar budaya antara kehidupan Katolik mereka dengan Amerika yang liberal, mungkin sudah cukup untuk membangun satu cerita sendiri. Tetapi, surat-surat Alicia berperan lebih besar lagi: ia berkisah tentang sebuah dunia yang ‘sakit’ di tengah benua Amerika sana.
Bagaimana, misalnya, ia harus merayu petugas pembagian makanan untuk mendapat bagian lebih. Bagaimana nama putrinya menghilang dari daftar tunggu rumah sakit hanya karena ia terlihat berdoa di gereja; bagaimana ia terpaksa melacur dengan sipir agar ia bisa menyampaikan surat dan kiriman barang untuk suaminya di penjara; dan lain sebagainya. Deskripsi yang ‘sakit’ dan menyedihkan ini — tak bisa tidak — sangat mengingatkan saya pada kisah Frankie McCourt di Angela’s Ashes.
Sebagaimana Frank McCourt dewasa pernah bertekad[1],
“Aku ingin pergi ke Amerika. Tempat di mana semua orang punya kakus dan bisa makan tiga kali sehari.”
Saya menjadi paham apa yang ada di benak Alicia, ketika berkata pada putrinya yang buta, Lucinda, bahwa ia pun ingin mereka pergi ke Amerika: tempat di mana “orang bisa terus mandi air panas dan punya tiga pasang sepatu”.
…
…
Mungkin, kalau saya bisa menyarikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, maka pesan itu adalah sebagai berikut: Menjadi pelarian revolusi di Amerika adalah hal yang berat. Tetapi, menjadi warga Kuba, yang tetap tinggal dan bertahan di bawah rezim yang menekan, adalah perjuangan yang lebih berat lagi.
***
Meskipun begitu, di samping berbagai kelebihan yang saya sebutkan di atas, novel ini sendiri bukannya tanpa kekurangan. Bagian menjelang endingnya terkesan rada over-dramatized[2] — dan ada satu-dua loophole minor yang, untungnya, tidak sampai mengganggu keseluruhan cerita[3]. 😕 Oh well. Saya rasa memang benar bahwa tak ada gading yang tak retak. ^^;
Ada juga kekurangan yang harusnya jadi tanggung jawab editor, bukan penulisnya sendiri. Yakni… banyak salah ketik. 😐 Mungkin karena masih cetakan pertama, sehingga proofreading-nya kurang mendetail… tapi sudahlah. Mengingat bahwa The Da Vinci Code cetakan pertama punya teman saya pun ternyata banyak salah cetaknya, kelihatannya saya tak bisa banyak protes. 😛
Conclusion
Sebagai penutup, saya pribadi menilai bahwa buku ini, terlepas dari berbagai kekurangannya, bisa dibilang sebagai karya yang sangat cemerlang. Saya belajar banyak hal tentang Kuba dari buku ini: cara makan mereka, pandangan rasisme terhadap kulit gelap dan campur, serta keadaan masyarakat di negeri pulau tersebut. Setidaknya hingga tahun 1970-an, dekade di mana kisah dalam buku ini akhirnya selesai.
Meskipun begitu, ada satu pelajaran yang paling berkesan yang saya tangkap dari novel ini.
Bahwasanya, orang-orang yang punya niat meninggalkan tanah air mereka — baik yang sudah eksil ataupun yang baru ingin eksil — bukanlah mereka yang dengan senang hati melakukannya. Ada romantisme yang terselip di situ. Dan, dalam novel ini, itu adalah kebahagiaan akan pantai berpasir putih, acara makan malam bersama paman dan bibi, serta makan arroz con pollo seusai berenang — hal-hal biasa yang, pada umumnya, baru terasa nikmat setelah jadi kenangan.
——
Catatan:
[1] Saya membaca kalimat ini pas nonton versi film Angela’s Ashes yang ditayangkan di TV. Saya belum pernah baca bukunya, soalnya — so there you have it. 😛
[2] Spoiler alert: (highlight to see)
IMHO, harusnya Nora dan Lucinda tak perlu sampai harus gagal mendapat kapal ke Jamaika di akhir kisah. Membuat mereka hampir mati terapung, rasanya kok rada terlalu melebih-lebihkan suasana yang sudah haru itu… tapi ini pendapat pribadi sih. ^^;
[3] Spoiler alert: (highlight to see)
Misalnya pada waktu sipir Ricardo berbohong bahwa Tony (suami Alicia) masih hidup, ketika (pada kenyataannya) Tony sudah ditembak mati dua tahun sebelumnya. Padahal Alicia dikisahkan selalu bertukar surat dengan Tony lewat sang sipir; harusnya dia sadar kalau tulisan tangan suaminya dipalsukan. Atau jika dia tidak mendapat surat selama dua tahun berturut-turut…
Narasi juga sempat menyebut nama “Manuel”, ketika Nora dan Lucinda hendak kabur bersama Jose Gomez lewat laut. Padahal waktu itu si nelayan belum menyebut nama aslinya.